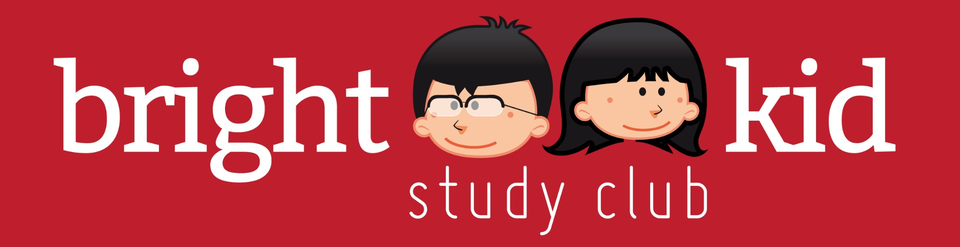oleh: Azzam Zhafir Ibrahim
Mahasiswa KPI UINSA Semester 6
Sejak digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Januari 2020 silam, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) disambut sebagai angin segar dalam dunia pendidikan tinggi. Dalam hal ini, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang menaungi lembaga Universitas Islam Negeri (UIN) di seluruh Indonesia. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diperkenalkan sebagai terobosan baru untuk mengubah wajah pendidikan tinggi di Indonesia. Tujuannya baik, agar mahasiswa bisa belajar lebih bebas, tidak hanya duduk di kelas, tetapi juga bisa belajar langsung dari dunia kerja, masyarakat, dan lingkungan profesional lainnya.
Melalui MBKM, mahasiswa diberi kesempatan untuk magang, terlibat dalam kegiatan sosial atau pengabdian masyarakat, menjadi pengajar di pelosok, atau bahkan kesempatan untuk student exchange merasakan menjadi mahasiswa di kampus unggul yang lainnya. Pemerintah berharap program ini bisa menjembatani kesenjangan antara pembelajaran di kampus dan kebutuhan di lapangan. Namun sayangnya, yang terjadi di lapangan sering tidak sesuai dengan harapan. Banyak mahasiswa merasa justru tidak mendapatkan pengalaman belajar yang berarti. Yang lebih menyedihkan, mereka justru merasa “tidak merdeka” sama sekali dalam program yang konon katanya membawa semangat “kemerdekaan” itu.
Salah satu masalah paling fundamental adalah kurang tepatnya pemilihan tempat magang mahasiswa dengan bidang keilmuannya dan pembagian jobdesk instansi kepada mahasiswa. Mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), misalnya, yang telah dibekali dengan keterampilan jurnalistik, broadcasting, komunikasi dakwah, dan keterampilan berbasis digital lainnya, justru memilih mitra di lembaga atau instansi yang tidak berkaitan sama sekali dengan kompetensi tersebut.
Ada yang ditugaskan di bagian administrasi, sebagai pengarsip data di kantor, bahkan menjadi service AC di sebuah mitra radio swasta dan masih banyak kasus yang sama lainnya. Praktik-praktik seperti ini tentu menurunkan ekspektasi semangat awal MBKM yang hendak menguatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan kebutuhan riil dunia kerja. Mahasiswa KPI yang seharusnya bisa menimba ilmu dari industri media, house production, lembaga dakwah, atau lembaga komunikasi publik sebagai public relation atau humas, malah terjebak dalam pekerjaan yang tidak mendukung pertumbuhan dari segi profesional mahasiswa. Mereka hanya menjadi “tenaga kerja magang” yang menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan administratif lembaga tanpa proses belajar yang menguntungkan.
Ironi lain yang dirasakan mahasiswa adalah beban kerja yang terasa terlalu mempressure dan tinggi. Dalam beberapa kasus, mahasiswa dituntut bekerja layaknya pegawai tetap datang pagi, pulang sore, melakukan pekerjaan rutin tanpa pengalaman praktik yang seharusnya relevan. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa bukan hanya membuang waktu belajar di kampus secara sia-sia, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mengeksplor diri sendiri karena energi dan waktu sudah terkuras habis untuk menyelesaikan pekerjaan yang tak sepadan dengan keahlian yang dimiliki.
Lebih menyedihkan lagi, sering kali instansi magang memberikan tugas atau perintah yang mengharuskan untuk mengeluarkan biaya pribadi dalam pekerjaannya. Bukankah lebih etis jika biaya juga dapat ditanggung oleh instansi. Sekali, dua kali memang wajar jika dibebankan pada mahasiswa, tetapi jika finansial dibebankan seterusnya kepada mahasiswa tanpa ada sokongan dari lembaga, bagaimana nasib mahasiswa. Tidak semua mahasiswa dibiayai oleh orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya apalagi mahasiswa rantau. Banyak diluar sana mahasiswa harus bekerja paruh waktu, bahkan full time untuk sekedar bertahan hidup di perantauan, agar orang tua tidak terlalu terbebani memikirkan hidup anaknya. Akhirnya, mahasiswa bukan hanya lelah secara fisik dan mental, tapi juga secara finansial.
Pertanyaannya, apakah kampus tidak tahu kondisi ini? Ataukah kampus sudah mengetahui tetapi memilih menutup mata dan bungkam karena telah menganggap MBKM hanya program yang harus dijalankan demi formalitas dan menjalankan amanat tugas kementerian?. Dalam pelaksanaan MBKM, idealnya kampus tidak hanya menjadi fasilitator yang hanya menyediakan, mengantar lantas menjemput, tapi juga sebagai pengawas akademik. Mahasiswa seharusnya dibekali pemahaman tentang visi program, keterkaitan dengan capaian pembelajaran (CPMK), serta didampingi secara aktif oleh dosen pembimbing lapangan.
Namun, yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang. Bimbingan dosen lapangan sangat minim. Komunikasi sebatas via WhatsApp, bahkan beberapa dosen nyaris tidak melakukan kunjungan lapangan. Ada yang hanya datang sekali di awal program untuk mengisi presensi mengantarkan mahasiswa atau menandatangani dokumen kehadiran, tanpa benar-benar melakukan proses pendampingan secara berkala untuk mahasiswa. Adapula yang hanya menjemput ketika proses magang telah usai, demi sebuah dokumentasi yang dianggap lebih besar pengaruhnya timbang pendampingan yang seharusnya dilakukan.
Dosen pembimbing lapangan juga sering terlalu sibuk dengan beban Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Akibatnya, mahasiswa merasa “ditinggalkan”, bekerja tanpa arahan, dan berjalan sendiri menghadapi tantangan di lapangan. Jika tidak ada inisiatif dari mahasiswa, program ini akan berlangsung sebagai rutinitas kosong yang tidak memberikan nilai tambah apapun.
Salah satu janji besar MBKM adalah konversi pengalaman di lapangan menjadi nilai mata kuliah. Artinya, waktu mahasiswa yang dihabiskan untuk praktik kerja tidak perlu diulang dalam bentuk mata kuliah reguler di kelas. Tapi kenyataannya, banyak mahasiswa yang mengikuti MBKM tetap diberi tugas tambahan mata kuliah yang semestinya patut dipertimbangkan penugasannya.
Hal ini tentu menjadi beban ganda. Mahasiswa sudah bekerja penuh di luar kampus, kurang mendapatkan pembelajaran yang relevan, dan tetap mendapatkan tugas tersendiri agar nilai tetap bisa dikonversikan. Pemberian tugas sebenarnya sah-sah saja diberikan kepada mahasiswa karena terdapat beberapa pengalaman yang memang sejak awal kurang sesuai dengan capaian mata kuliah sehingga kurang relevan jika dikonversikan. Namun, yang sangat disayangkan ada beberapa penugasan yang diberikan kepada mahasiswa dalam kondisi mendadak dan kurang masuk akal.
Ada dosen yang memberikan tugas dalam bentuk membuat video iklan layanan masyarakat yang sejatinya ada maksud tersendiri dan berbau politis. Maka dari itu, MBKM yang bertujuan agar mahasiswa mampu mandiri dan belajar ke dalam ranah industri serta sudah siap ketika nantinya akan memasuki dunia profesional malah memberikan beban ganda. Menjadi jebakan akademik yang justru kontraproduktif.
Lantas timbullah pertanyaan: siapa yang benar-benar diuntungkan dari pelaksanaan MBKM ini? Mahasiswa jelas kurang mendapatkan manfaat yang maksimal. Mereka lelah, harus memenuhi kriteria yang ditentukan agar relevan secara akademik, mengeluarkan biaya pribadi, dan tetap mendapatkan tugas tambahan.
Dosen? Dalam banyak kasus, juga tidak sepenuhnya diuntungkan karena harus menjalankan peran tambahan dengan insentif yang tidak memadai. Apalagi jika mahasiswa mereka tersebar di banyak instansi, maka beban koordinasi menjadi semakin rumit.
Kampus? Mungkin mendapat poin dan data tambahan untuk akreditasi atau reputasi positif karena telah “melaksanakan” MBKM. Tetapi jika pelaksanaannya hanya menjadi program simbolik, maka capaian tersebut semu belaka. Yang benar-benar diuntungkan bisa jadi adalah instansi tempat magang yang mendapat tenaga kerja tambahan secara cuma-cuma tanpa kewajiban membimbing secara pedagogis.
Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan MBKM, terutama di lingkungan PTKIN seperti UIN. Pertama, kampus harus menjalin dan memastikan kemitraan dengan instansi yang relevan secara akademik dan profesional dengan program studi mahasiswa. Kedua, dosen pembimbing lapangan harus diberi pelatihan dan dukungan agar bisa melakukan pengawasan dan evaluasi secara substansial, bukan administratif semata.
Ketiga, sistem konversi nilai harus dibuat transparan, adil, dan berbasis pada capaian pembelajaran yang nyata di lapangan. Keempat, setidaknya kampus mampu menyediakan dukungan baik dalam bentuk logistik maupun materi agar mahasiswa tidak menanggung beban sendiri dan mahasiswa merasa terarahkan. Dosen pembimbing dan pihak program studi sebaiknya welcome terhadap keluhan atau hal yang sedang dialami oleh mahasiswanya, tidak sekedar memberikan perintah. Namun, juga mampu mendengarkan dan memberikan saran solutif agar mahasiswa merasa didampingi dan tidak salah langkah. Terakhir, mahasiswa juga perlu dilibatkan dalam perancangan program MBKM agar kedepannya pelaksanaan MBKM semakin baik dan berjalan lancar dengan semestinya.
Merdeka Belajar adalah gagasan besar, sebuah terobosan baru. Tapi sama seperti semua gagasan besar, bisa gagal bila dijalankan tanpa kesadaran, tanpa empati, dan tanpa keterlibatan penuh semua pihak. Jika mahasiswa sebagai subjek utama justru merasa terpinggirkan, dibebani, dan tidak mendapatkan apa-apa, maka MBKM telah gagal secara etis dan ilmiah.
Sudah saatnya kampus tidak hanya “melaksanakan” MBKM sebagai program formalitas tahunan semata, tetapi juga “menyelenggarakan” secara sungguh-sungguh dengan mendengar aspirasi mahasiswa, memperbaiki sistem, dan mengawal setiap langkah. Karena pendidikan tidak boleh berhenti pada sebuah slogan yang berulang diteriakkan akan suksesi keberhasilannya. Pendidikan harus didorong untuk menjadi ruang kebebasan dalam mengekspresikan segala hal selama dalam batas kewajaran. Dan “merdeka belajar” harus benar-benar menghadirkan kemerdekaan yang utuh: di dalam pikiran, dalam ruang belajar, dan dalam dunia kerja. (*)